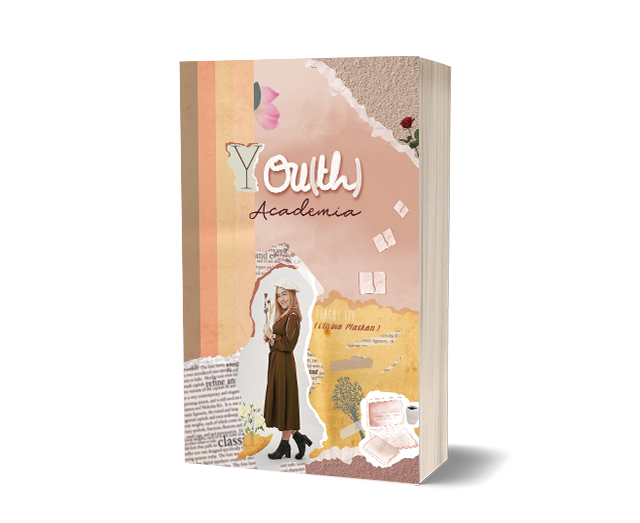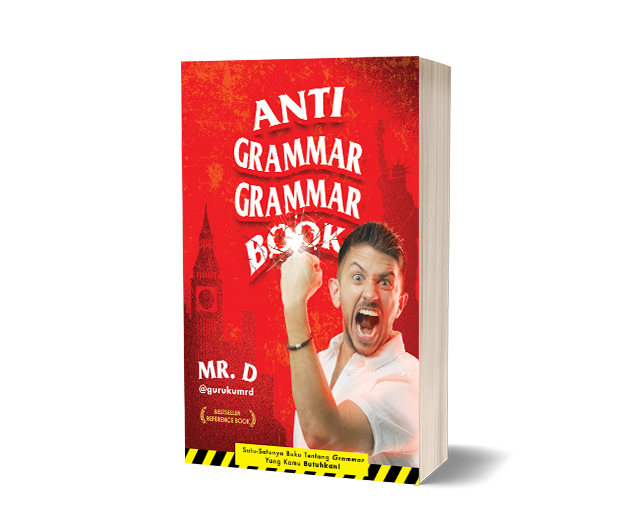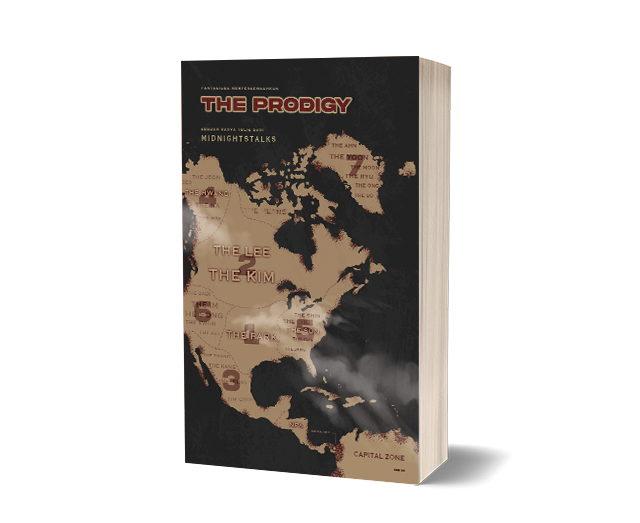Deskripsi
Penulis: Dhannisa Dwilagustino (DHANNISA CHO)
ISBN: Sedang diajukan
e-ISBN: Sedang diajukan
Kertas: Bookpaper 52 Gram
Ukuran: 13 x 19 cm / Doff
Jumlah Hal: BW 242 Halaman
PROLOG
Sebelum aku setenang ini dalam menjalani kehidupan sebagai orang dewasa, aku pernah berkali-kali meminta kematian pada Tuhan. Bukan karena aku membenci hidup, tapi karena aku tidak tahu harus bagaimana menjalaninya. Usiaku masih terlalu muda untuk memahami arah hidup dan tanggung jawab. Aku hanya ingin berhenti memikirkan segalanya sendirian.
Masa kecilku terasa seperti pemakaman yang tidak dihadiri siapa pun. Sunyi, dingin, dan penuh kehilangan. Kerinduanku akan pelukan lembut bermula dari rumah yang tidak pernah benar-benar menjadi rumah.
Di sana, gema pintu yang dibanting, teriakan yang menggema, dan isakan pilu yang terekam dinding menelan tawa serta kebahagiaan yang dulu pernah ada. Dan untuk waktu yang lama, aku pikir semua rumah memang seperti itu—bahwa rasa takut harus lebih dulu ditanggung agar cinta bisa kembali muncul.
Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk disayangi, aku harus menanggung sakit dan terus berusaha. Menahan perih dalam mengejar pencapaian dan menjadi ‘anak baik’ adalah bahasa satu-satunya yang kupahami agar bisa merasakan sedikit kasih dan penerimaan.
Namun, luka itu tidak pernah pergi. Ia tinggal, mengeraskan hatiku dan membakar orang-orang di sekitarku. Kepahitan itu tumbuh di sana—di tempat yang seharusnya dipenuhi kelembutan.
Aku hanyalah seorang anak yang dianggap baik karena dewasa sebelum waktunya. Aku adalah anak yang harus menahan lidahnya agar tidak menambah beban siapa pun. Anak yang menyakiti dirinya sendiri untuk menahan amarah, agar bisa mengeluarkan rasa perih yang berusaha ia sembunyikan. Namun, tidak ada rasa sakit pada fisikku yang mampu menandingi luka yang tinggal jauh di dalam hatiku.
Dan itu ironis, karena dulu—sebelum semuanya—aku adalah anak yang baik. Aku manis. Yang kuinginkan hanya bermain boneka, melukis, berlari di luar, dan makan permen. Namun, kelembutan bukan pilihan di rumah tempatku tumbuh. Amarah dan perjuangan orang tuaku menuntutku untuk kuat, mengeraskan diriku—atas nama bertahan hidup.
Dan ketika aku dewasa, aku mencari kelembutan itu di luar sana—pada diri orang asing. Aku jadi bertanya-tanya, adakah seseorang yang mau memelukku apa adanya? Yang tidak takut dengan dalamnya lukaku, yang melihat kerapuhanku sebagai sesuatu yang indah—bukan aib yang harus dihapus.
Sekarang, aku masih belajar untuk bernapas tanpa rasa cemas. Masih belajar untuk tidak selalu waspada atas hal buruk yang akan terjadi. Masih belajar mengalir seperti air—seperti seharusnya aku dulu. Masih mencoba percaya bahwa diam tidak selalu berarti bahaya. Belajar untuk sekadar menjadi seperti diriku yang seharusnya.
Namun, di sela-sela ketenangan itu, ada saat-saat ketika kenangan buruk datang menghampiri. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, kapan duka ini berakhir—jika pemakamannya tidak pernah diadakan dan mereka yang menyebabkannya tidak pernah benar-benar mendampingiku untuk berduka?
Mungkin jawabannya masih tersembunyi di masa lalu—di antara potongan kenangan yang sering kali muncul tanpa diundang. Semakin besar, aku semakin belajar bahwa ada pelajaran, kenangan dan jawaban dalam cara kita dibesarkan, tentang bagaimana kasih sayang dan kehilangan secara tidak sadar mungkin diperkenalkan sejak dini, yang diam-diam membentuk cara kita menanggung hari ini.
***
Dulu, saat usiaku masih 5 tahun, aku sering sekali berlari ke depan pintu rumah masa kecilku untuk menyambut ayah dan ibu yang baru saja pulang. Suara motor mereka, untaian kunci yang dijinjing, hingga langkah berat nan lelah masih terekam jelas di kepalaku. Suara-suara itulah yang biasanya membuatku semangat untuk keluar dari selimut.
Banyak hal yang ingin kubagikan pada mereka. Tentang hariku, episode baru kartun kesukaanku, hal konyol pada rambutku, aduan tentang menyebalkannya adik dan nenekku, dan masih banyak lagi.
Bertambahnya usia, aku seringkali bertanya-tanya, apakah mereka mengingat hal-hal kecil itu? Apakah mereka juga merasakan perasaan sedih dan rindu yang sama sepertiku? Terlebih ketika mereka pulang ke rumah, tapi tidak lagi ada aku atau adik-adikku yang menyambut seperti dulu.
Bertahun-tahun, aku merasa perasaan ini selalu menjadi jangkar untukku. Yang menahan dan memberatkan langkahku. Aku ingin bebas. Aku ingin kehidupan yang bebas. Kehidupan yang lembut. Kehidupan yang tidak terikat. Sayangnya, ke mana pun aku melangkah, sejauh apa pun aku berlayar, sekuat apa pun aku berusaha melawan arus, jangkar ini selalu menahanku jauh di bawah air.
Seumur hidupku, rasanya aku hanya bertahan. Tidak hidup sepenuhnya. Selalu bermimpi dan berdoa untuk kehidupan yang baik, lembut, dan berpihak kepadaku. Aku selalu menginginkan kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, kasih sayang, kenyamanan, tawa, dan kebahagiaan. Aku ingin dikelilingi dengan ketenangan dan kebaikan.
Melihat matahari terbit dan kembali lagi terbenam. Meminum es kopi kesukaanku, membaca buku tanpa tergesa-gesa, merasakan hujan dan panas di kepalaku. Aku hanya ingin merasa aman dan disayang untuk dapat melakukan semua itu. Aku ingin kehidupan yang lamban di mana aku bisa bernapas tanpa tekanan siapa pun. I want a gentle life.
Dan aku tidak bisa mendapatkan itu semua, karena walaupun aku ingin bebas, sebagian besar diriku tetap tinggal bersama kedua orangtuaku. Aku masih ada di rumah masa kecil itu, menunggu mereka pulang, menunggu untuk disayang. Tapi, sekarang aku sudah besar, aku bukan lagi anak berusia 5 tahun yang sering berlari dan berdiri di depan pintu menanti mereka.
Jalanku memang lebih beruntung dibanding kedua orangtuaku. Tapi, sepertinya aku tidak lebih baik daripada mereka. Terutama dalam pengasuhan. Ternyata, punya anak itu, artinya punya tanggung jawab dan amanah yang besar. Naifku hanya melihat apa yang tidak ada di kedua orangtuaku dan menjadikan itu sebagai satu-satunya standar yang setidaknya harus aku lewati dalam menjadi orangtua. Padahal nafkah anak bukan hanya soal yang terlihat. Hadirku, kupingku, pelukanku, sabarku, bantuanku, mainku bersamanya, tuntunanku, dan penerimaan lapang dadaku. Sayangnya, aku masih lalai terhadap semua itu. Rasanya, selama ini semua orang selalu mengira aku tidak butuh bantuan. Paling kuat dan pasti selalu bisa diandalkan. Padahal... semuanya harus aku cari tahu sendiri. Ke sana, ke sini, bingung, sedih, capek. Gagal, bangkit, dan belajar lagi, itu semua kulakukan sendiri.
Aku percaya, bahwa parenting adalah tentang mengendalikan kelakuanku sendiri dan menjadi orang dewasa yang sadar akan tanggung jawabnya. Namun, rasanya tidak dengan kedua orangtuaku dulu. Tidak dengan ibuku. Sepertinya, bagi mereka parenting adalah tentang mengendalikan kelakuanku sebagai anak yang begitu diharapkan kesuksesannya. Mereka melatihku menjadi dewasa, sebelum waktunya.
***
Penulis